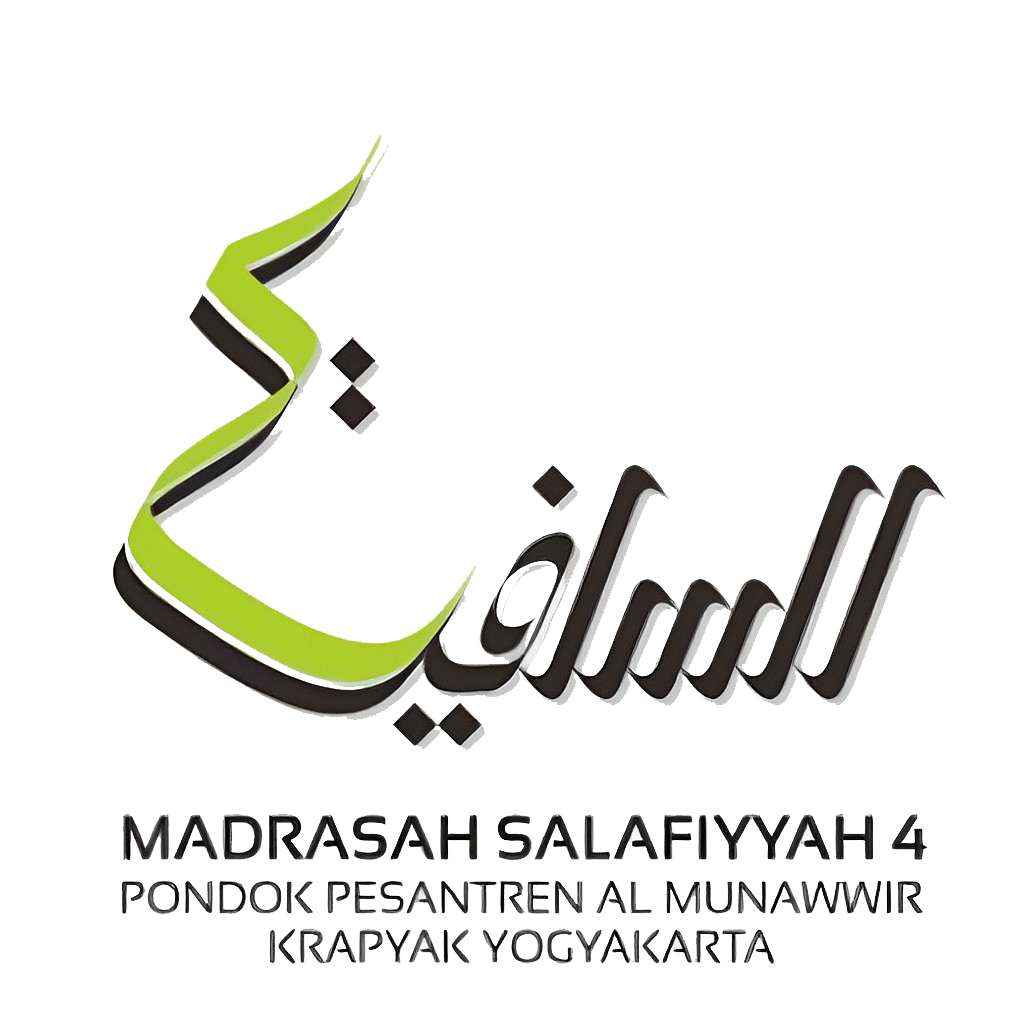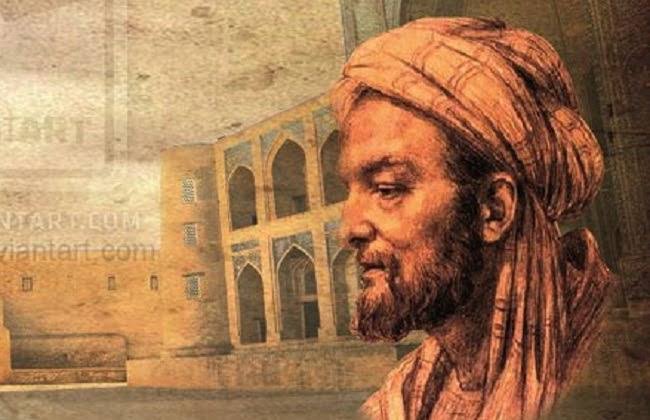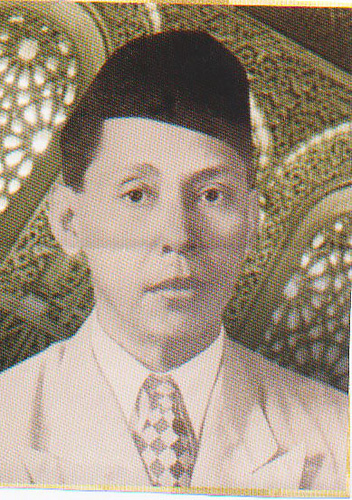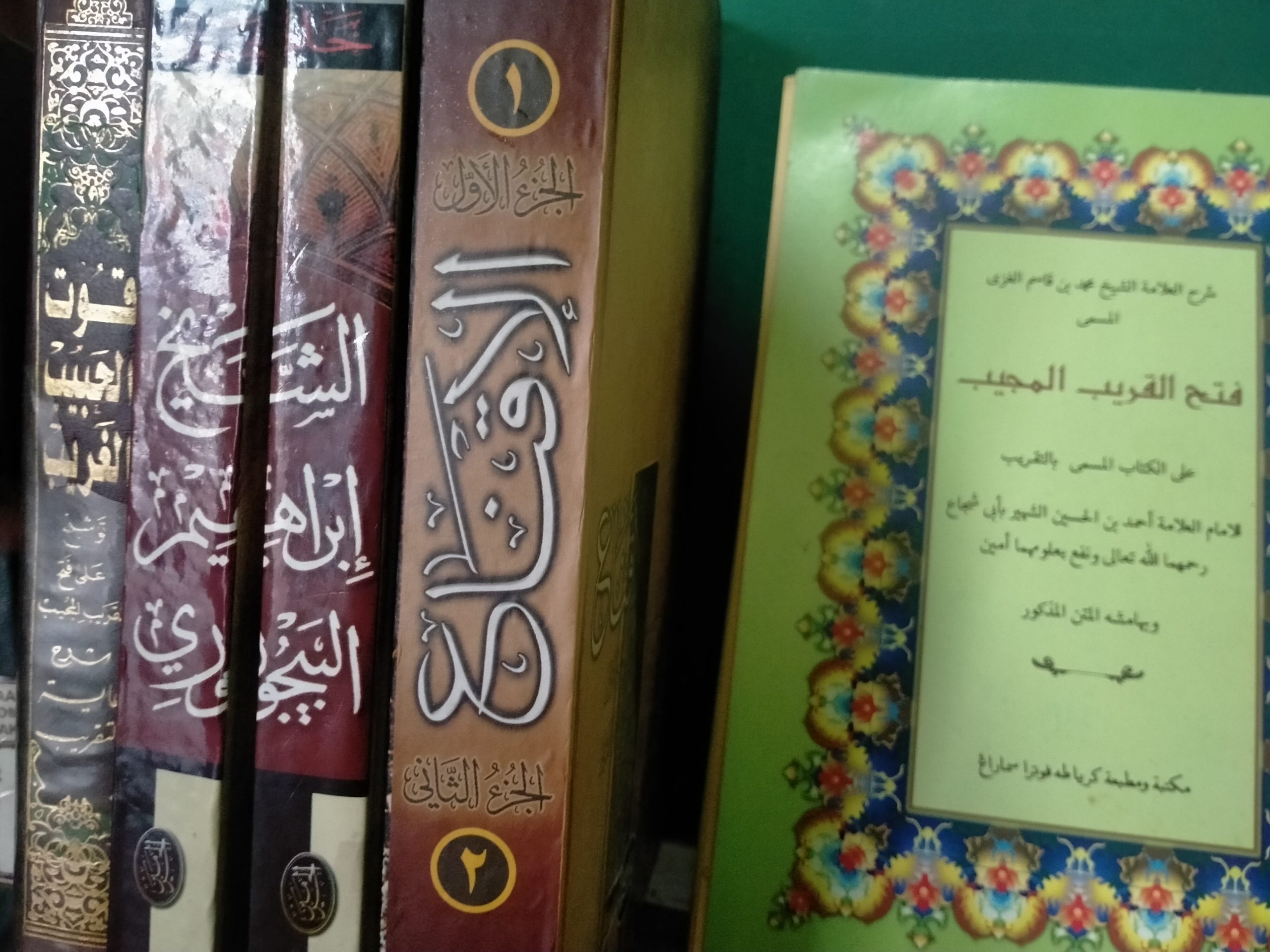Oleh: Chanif Ainun Naim
“The more he identifies with the dominant images of need, the less he understands his own life and his own desires. The spectacle’s estrangement from the acting subject is expressed by the fact that the individual’s gestures are no longer his own; they are the gestures of someone else who represents them to him.”
― Guy Debord, The Society of the Spectacle ―
Jika kita belajar tasawuf, dalam tasawuf itu ada aspek teoretis (nadzari) ada juga aspek praksis (‘amali). Aspek teoretis pastinya mencakup bagaimana cara pandang tasawuf terhadap dunia (world view), begitu juga dalam filsafat sosial. Filsafat Sosial sebagai sebuah teori filsafat pun memiliki cara pandang tersendiri dalam menjelaskan dunia. Tulisan kali ini akan mencoba melihat cara pandang teori sosial yang diinisiasi oleh Guy Debord tentang kehidupan yang disebutnya sebagai the society of the spectacle serta cara tasawuf bersikap terhadap dunia yang berupa kesenangan yang menipu daya belaka (mata’ al-ghurur).
Kita mulai dari apa itu masyarakat spectacle atau masyarakat tontonan (society of spectacle). Guy Debord, salah satu pemikir Marxis (Marxist theorist) dari Perancis, melihat bahwa abad ke-20 adalah abad dimana alienasi (keterasingan) manusia mencapai puncaknya, atau abad dimana komodifikasi sebagai inti dari kapitalisme telah mencapai titik kulminasi. Lalu sebenarnya apa sih alienasi itu? Nah, dalam tradisi Marxian, alienasi adalah kondisi dimana manusia terasing sebagai akibat dari jerat sistem kapitalisme. Situasi ini membuat manusia tidak lagi mengenali dirinya sendiri, pekerjaannya, hasil kerjanya dan tidak mengenali sesamanya. Empat keterasingan itu adalah:
- Terasing dari dirinya sendiri. Sebenarnya, manusia bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (dlaruriyyat) sebatas agar ia dapat menyambung kehidupan. Jadi, tidak ada itu, istilah menumpuk kekayaan (al-takatsu fi al-mal). Tapi, oleh kapitalisme, manusia lalu bekerja bukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja, tetapi dia bekerja hingga melebihi batas jam kerjanya itu karena tertunduk dan dipaksa oleh kecenderungan untuk al-takatsuru fi al-mal itu atau menumpuk surplus value-nya itu. Sehingga menghasilkan apa? Manusia menjadi bukan dirinya (alienation). Manusia menjadi semacam skrup bagi mesin besar itu agar tetap berjalan. Lalu apa akibatnya? Menjadi workaholic, lalu stress dan pantaslah tema mental illness sekarang menggaung.
- Akibatnya adalah, bahwa karena manusia bekerja bukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya semata, maka manusia terasing dari aktivitasnya, dimana aktivitasnya justru ‘ditujukan untuk melawan dirinya sendiri’, seolah-olah aktivitas itu ‘bukan miliknya’. Dia bekerja bukan untuk membuat karya tetapi dia bekerja karena terpaksa.
- Sehingga, hasil karyanya bukan lagi karyanya. Manusia terasing dari sesuatu yang menjadi hasil kerjanya, dan tidak bisa menikmati hasilnya itu.
- Dalam sistem itu, manusia menjadi tidak mengenal dengan sesama manusia. Karena apa? Karena manusia dan hubungan dia dengan manusia lain di lingkungan dia bekerja hanya sebatas sebagai sesama orang yang asing, bukan sesama manusia yang utuh.
Karena terjadi proses alienasi itu, maka inilah yang disebut sebagai suaru proses dehumanisasi, kata Marx, dimana secara perlahan, manusia diajak untuk menjadi orang lain, menjauh dari mengenali dirinya. Kesadaran (consciousness) terjadi ketika manusia tau apa yang terjadi padanya, apa yang seharusnya dan apa yang harus dilakukan. Atau dinamakan dengan sadar kelas. Tapi tenang saja, itu dulu sekali. Itu terjadi di masa lalu, masa fordisme. Kalau sekarang, masa paskafordisme? Lebih ancur-ancuran.
Dunia Hanyalah Sandiwara: The Society of the Spectacle
Ada apa setelahnya? Lebih lanjut, masyarakat spectacle atau masyarakat tontonan adalah kondisi di mana seluruh manusia telah diokupasi, telah dikuasai sepenuhnya oleh komoditas. Masyarakat tontonan adalah puncak ilusi dari sebuah komunitas, dimana orang dianggap utuh jika telah melakukan ‘pemenuhan total’ dengan mengonsumsi barang-barang yang telah dikomodifikasi. Debord mendeskripsikan istilah tontonan sebagai ‘refleksi visual dari rezim ekonomi pasar’. Ketika kebutuhan ekonomi digantikan oleh kebutuhan ‘pembangunan’ yang tak terbatas, maka kepuasan manusia atas kebutuhan dasarnya (dlaruriyyat) digantikan oleh pemenuhan kebutuhan semu nan tiada henti. Jika dulunya orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan primernya, kini, dalam masyarakat yang dipenuhi komoditas, dipertontonkan dalam bentuk visual. Aktivitas konsumsi pun telah menjadi “kewajiban” baru.
“… just as early industrial capitalism moved the focus of existence from being to having, post-industrial culture has moved that focus from having to appearing”
“Kapitalisme industri awal memindahkan fokus keberadaan dari keberadaan menjadi memiliki, budaya pasca-industri telah memindahkan fokus itu dari memiliki menjadi untuk tampil.”
(Guy Debord, The Society of the Spectacle, 2002)
Artinya apa? Artinya adalah bahwa segala yang nampak oleh kita di realitas kita yang utamanya diperlihatkan oleh media, baik media massa maupun media sosial dan bahkan hubungan antar sesama manusia adalah menunjukkan bahwa manusia secara keseluruhan telah sepenuhnya dikuasai oleh logika pasar yang telah menguasai berbagai hubungan sosial, seperti terjadi dalam realitas kita sekarang ini. Manusia melihat berita, manusia melihat iklan, manusia melihat realitas sekitarnya yang dilihat hanyalah sebentuk tampilan atas konsumsi-konsumsi benda-benda. Lalu mereka seakan digerakkan untuk mengonsumsinya juga. Mereka lalu mengumpulkan uang, bukan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi lebih dari itu, manusia secara logika telah tertuntut mengkonsumsi segalanya, mengkonsumsi apapun yang dia lihat setalah menginternalisasinya. Penyesuaian dengan kondisi yang demikian menghasilkan manusia sebagai komoditas. Artinya apa? Komoditas bukan lagi hasil produksi, tetapi kehendak untuk konsumtif pun dikomodifikasi. Menuruti semuanya, menyebabkan dehumanisasi secara mental dan fisik pada konsumen.
Mbulet, ya? Gampangnya begini, deh, saya beri contoh: dalam bidang teknologi, ada yang namanya gadget, contoh saja handphone. Ada sebuah merk yang rutin mengeluarkan produk terbaru, dipertontonkan lewat iklan di televisi, reklame di jalanan, feed influencer Instagram, tweet selebtweet, tetangga komplek membelinya, teman tongkrongan membelinya, lalu orang-orang membicarakannya, di kolom komentar, di tongkrongan, di grup WhatsApp keluarga, bahkan di momen-momen makan malam bersama keluarga, dan sebab orang-orang terhipnotis bahwa produk itu mengerek nilai tertentu jika dipertontonkan, maka kamu pun tergerak untuk memilikinya. Kamu lalu bekerja, dari pagi sampai pagi lagi, bekerja sekuat tenaga, sampai mengabaikan keluargamu, lembur sampai mengabaikan dulu tongkrongan di lingkunganmu, makan pun kalau ingat, kesehatanmu nomor sekian, asam lambungmu yang akut itu kamu jadikan kekasih, kalau bisa setiap hari hadir itu asam lambung, hanya supaya kamu bisa membeli handphone itu. Itu, tuh, apa yang kamu kejar, Dik?
“Where the real world changes into simple images, the simple images become real beings and effective motivations of hypnotic behavior.”
“Saat dunia nyata berubah menjadi gambar sederhana, gambar sederhana menjadi makhluk nyata dan motivasi efektif untuk perilaku hipnosis.”
(Guy Debord, The Society of the Spectacle, 2002)
Jadi rasionalisasinya begini, melalui rentetan komoditas yang mulai mewakili kehidupan mereka, penonton dihadapkan pada contoh-contoh ideal (untuk meng-‘ada’ sebagai manusia) yang mereka perjuangkan untuk dicapai dan dikonsumsi tanpa henti. Penonton dimanipulasi sedemikian rupa sehingga apa yang terlihat menjadi lebih penting dan menarik. Kini, orang harus memakai produk-produk tertetu untuk meningkatkan ketampanannya, kecantikannya, dan status sosialnya di tongkrongannya. Jika kamu juga demikian, maka Debord mengejekmu begini: “Young people everywhere have been allowed to choose between love and a garbage disposal unit. Everywhere they have chosen the garbage disposal unit”. Kamu diizinkan untuk memilih antara cinta dan sampah, tapi kamu kok malah memilih sampah.
Orang melihat influencer memakai produk kecantikan, lalu ia mencobanya. Orang melihat temannya memakai produk paling baru, lalu dia merasa ingin mengenakannya juga. Jadi dia bekerja keras mengabaikan kesehatannya semata untuk menjadi konsumtif, termotivasi mengenakan apapun yang dianggap trendi, semata agar tidak dilihat ketinggalan jaman. Inilah masyarakat spectacle, yang secara total menhunjam dalam ke dalam sendi-sendiri kehidupan. Kita seakan menjadi anak hilang, mencari-cari tanpa tahu apa yang dicari, mengejar sesuatu yang memang tidak ada habisnya, sebab ia semu, “like lost children we live our unfinished adventures”.
Hari ini seseorang bekerja bukan karena ingin mengaktualisasi diri, tetapi sekadar mencari upah yang digunakan untuk memenuhi hasratnya membeli komoditas. Dengan menjadi workaholic, para pekerja berharap bisa menjadi kaya dan lebih kaya lagi. Meskipun, secara paradoksal, mereka bekerja hingga lembur untuk bisa menikmati “liburan”. “Behind the masks of total choice, different forms of the same alienation confront each other.” “Di balik topeng pilihan total, berbagai bentuk keterasingan yang sama saling berhadapan”. Proses tontonan menuntut penggunaan citra perantara yang tidak hanya mempromosikan barang untuk dijual, tetapi juga memasarkan fantasi tambahan. Fantasi inilah yang telah mengubah tubuh-tubuh penonton menjadi sekadar mesin hasrat nan konsumtif.
Dunia yang kita diami ini tidak ada tujuannnya sama sekali, Kata Debord, “Goals are nothing, development is everything. The spectacle aims at nothing other than itself”. Di waktu luang, pekerja memiliki peran baru nan mulia sebagai konsumen; sekadar ATM berjalan yang kehidupan pribadinya disuguhi ‘opium’ berupa fesyen, gawai, kendara, kuliner hingga properti. Kata Debord, “orang yang mempersonifikasikan sistem memang terkenal karena tidak seperti yang terlihat; mereka telah mencapai kebesaran dengan merangkul tingkat realitas yang lebih rendah daripada tingkat kehidupan individu yang paling tidak penting ―dan semua orang mengetahuinya”.
“In our society now, we prefer to see ourselves living than living.” Dalam masyarakat kita sekarang, kita lebih suka melihat diri kita sendiri hidup daripada hidup. Lalu, bagaimana agar hidup kembali hidup? Agar bisa menghidupi kehidupan? Agar kembali utuh menjadi manusia? Menjadi diri sendiri? Kesadaran itu adalah dengan nulayani keumuman itu sendiri. Siapa yang ikut arus, niscaya dia akan hanyut dalam kepalsuan yang niscaya.
Bertasawuf untuk Menjelaskan dan Mencari Jalan Keluar
Jika melihat uraian di atas seakan-akan hidup kemudian menjadi sangat tidak bermakna, hidup menjadi seperti tidak ada artinya, bahwa untuk menjadi manusia yang utuh, hal sudah sangat jauh dari gapaian. Bila tidak jeli, sseorang akan jatuh dalam ceruk keputusasaan, pesimis terhhadap kehidupan dan menganggap bahwa tidak ada makna sama sekali dari hidup ini. Tetapi, di sinilah gerak tasawuf menemukan jalannya, sebab inti dari tasawuf adalah sebuah perjalanan untuk mengenali diri sendiri, “man ‘arafa nafsah faqad ‘arafa rabbah”; siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Pengenalan diri adalah sebuah proses hati, sebuah pergumulan tiada henti tentang hati. Realitas memang tidak akan pernah bisa diubah, tetapi kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap realitas dan cara pandang dimulai dari hati, sebab hati adalah posisi inti dari sebuah kesadaran, perasaan, keinginan dan bahkan kebahagiaan; sebuah kesadaran kosmik, kesadaran tentang manusia, alam semesta dan Tuhannya. Dengan demikian, maka mafhum jika tasawuf sebagai ilmu itu progresif degan wataknya yang dinamis.
Tidak menherankan pula bahwa tasawuf itu adalah sebuah proses kegairahan spiritual (al-tsaurah al-ruhaniyyah). Tasawuf secara umum berbeda dengan akhlak atau etika. Etika bisa dilakukan tanpa adanya landasan ilmu ketuhanan tertentu, tetapi tasawuf sebagai sebuah teori, dia memiliki aspek teoretis (nadzari) dan aspek praksisnya (‘amali). Aspek teoretis dari tasawuf berkaitan dengan pemahaman tentang wujud, yakni tentang Tuhan, manusia dan alam semesta. Sedangkan aspek praksis tasawuf berkaitan dengan tata cara hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia lain, alam dan dengan Tuhan sebagai hasil dari pemahaman tertentu dari teori tasawuf. Antara tasawuf sebagai teori dan praktif, keduanya harus berjalan beriringan untuk mencapai kesempurnaan sebagai manusia (insan al-kamil). Metode yang digunakan adalah pembersihan jiwa (tazkiyat al-nafs) dengan serangkaian mujadadah al-nafs dan riyadlah al-nafs. Keseluruhan proses untuk menuju kesempurnaan sebagai manusia ini disebut dengan suluk, sebuah perjalanan menuju Allah.
Dalam suluk tersebut, seseorang harus meniti maqamat (kedudukan seorang pejalan spiritual; salik di hadapan Allah) tertentu. Setiap salik dalam prosesnya juga akan mengalami ahwal tertentu (suasanan atau keadaan yang menyelimuti kalbu). Perjalanan yang ditempuh oleh salik dalam prosesnya menuju Allah ini akan melalui tiga pos (marhalah) sebagai maqam tertentu, dengan mujahadah dan riyadlah tertentu serta dengan ahwal tertentu. Ketiga marhalah tersebut adalah: takhalli, tahalli dan tajalli. Secara singkat, ketiga marhalah itu dijelaskan sebagai berikut:
- Takhalli: artinya adalah mengosongkan. Mengosongkan apa? Mengosongkan hati. Dari apa? Dari keinginan-keinginan, motivasi-motivasi dan segala hal yang tidak karena Allah. Dalam marhalah ini, ada tiga hal yang harus dilalui, yaitu taubat (dari segala dosa), wara’ (menjaga diri dari melakukan dosa), ‘iffah (menjaga diri dari segala macam pengharapan kepada orang lain), zuhud (menghindari ketergantungan, pengharapan dan kecintaan pada selain Allah). Jika seorang salik telah melewati pos ini, maka dia akan berjalan menuju pos selanjutnya, yaitu;
- Tahalli: artinya adalah menghiasi. Menghiasi apa? Menghiasi dan mengisi hati. Dengan apa? Dengan sifat-sifat yang baik, dimulai dengan sabar (dari melakukan maksiat, dalam menjalani ketaatan dan dalam menghadapi ujian hidup), tawakkal (menjalankan segala sesuatu semata dengan motivasi karena Allah, dan bergantung hanya kepada Allah dalam proses perjalanan hidup), ridla (menerima segala hal yang terjadi dalam hidup atau qana’ah; nrimo ing pandum, dan menyadari bahwa segala yang terjadi dalam hidup adalah semata kehendak Allah), dan syukur (menyukuri segala yang diberikan Allah dalam hidup). Jika salik telah melewati kedua pos di atas, maka dia akan menginjak pada perjalanan selanjutnya, yaitu;
- Tajalli: artinya penjelmaan, manivestasi. Dengan apa? Para sufi mengartikannya dengan al-takhallaq bi akhlaqillah, berperilaku dengan “perilaku” Allah. Artinya bagaimana? Ada dua kondisi yang akan dialami oleh salik, yaitu thuma’ninah (tidak gelisah) dalam menjalani hidup, mahabbah (dipenuhi cinta). Sehingga, Allah adalah Dzat yang rahman al-dunya wa al-akhirah; maha pengasih bagi seluruh makhluk di dunia dan di akhirat. Dengan berperilaku dengan perilaku Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka seseorang akan mempraktikkan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah.
Para sufi berbeda-beda dalam mendefinisikan serta mengklasifikasi maqamat apa saja yang harus dilalui, ahwal apa saja yang akan dialami serta dengan metode bagaimana. Sebab ini adalah ilmu tentang kondisi hati (al-‘ilm bi ahwal al-qalb), maka sangat sulit menjelaskannya secara sitematis. Sehingga, pelan-pelan dilalui saja berdasarkan kata kuncinya dengan permenungan yang panjang.
Aduh, kok sepertinya sulit, ya? Dan apa korelasinya dengan the society of spectacle? Bila judulnya cara tasawuf menjawab problem sosial itu, dimana letaknya? Bukankah bekerja adalah juga sebuah keharusan? Bila kondisi sudah demikian, lalu harus bagaimana? Bertapa di puncak gunung? Lha wong puncak gunung saja jadi komoditas? Mau apa lagi yang bisa dilakukan?
Kata kuncinya adalah di ―meminjam istilah Aa Gym―manajemen qalbu. Motivasi, interest, keinginan, harapan, atau khawathir, munculnya dari hati. Orang harus bergerak, bekerja, berkrasi, sebab itu adalah perintah Tuhan kepada manusia; wa qul: i’malu fasayarallahu ‘amalakum wa rasuluhu wa al-mu’minun, dan katakanlah, “bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin”. Tapi niatkan itu semua karena Allah. Sehingga hasilnya seberapapun, itu adalah pemberian Allah yang baik untukmu, lalu kamu akan dijauhkan dari perasaan susah, gelisah, menggerutu, dan marah serta menyalahkan pihak tertentu, seraya tetap mengamalkan apa yang harus dilakukan oleh salik di atas. Dengan mendasarkan segalanya semata karena Allah, maka melihat kegaduhan apapun di masyarakat, kamu tidak lantas kaget, gagap dan bahkan latah. Sehingga dengan demikian, kebahagiaan dan kesedihan, nikmat dan musibah, sempit dan lapang, pujian dan cacian, penghormatan dan penghinaan, sanjungan dan pengucilan, semuanya adalah sama. Lalu, semoga Allah menganugerahkan perasaan ridla pada segala ketentuannya, qana’ah atas pemberian-Nya, sabar atas ujian-Nya, dan thuma’ninah dalam hidup dan pada akhirnya, dianugerahi untuk mengenal-Nya; man ‘arafa nafsahu faqad ‘arafa rabbahu. Pahamilah, renungkanlah, dan jalanilah, Nif, Chanif Ainun Naim! Ini wejangan untukmu []
Sumber Gambar: https://medium.com/@matanshapiro/cryptogenesis-the-society-of-the-spectacle-in-the-cryptocurrency-ecosystem-f258c92a5da8